MUI Minta Pastikan RUU P-KS Tak Bisa Dijadikan Dalih LGBT
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan, harus dipastikan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tak bisa dijadikan dalih pembenaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta perzinaan.
Anggota Komisi Fatwa MUI, Badriyah Fayumi menyampaikan, MUI memberikan pandangan khusus untuk memastikan agar RUU P-KS tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen masyarakat dan bangsa yang lebih berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
Ia menyebutkan beberapa hal penting yang menjadi penekanan pandangan MUI dalam RUU ini. Antara lain, pertama, perubahan dan penyederhanaan definisi agar tidak multitafsir; kedua, penyederhanaan dan penjelasan bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual agar mudah dipahamai dan tidak multitafsir, terutama oleh Aparat Penegah Hukum.
Ketiga, tidak ada kriminalisasi hubungan suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama; keempat, perhatian yang besar pada aspek pencegahan dengan memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama, dan edukasi pencegahan perlu disampaikan dalam bahasa agama selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.
Kelima, norma-norma yang ada dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (al-mukrah atau al-madhghuth).
“Dan RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih pembenaran perilaku seks sejenis dan zina,” tegas Badriyah dalam acara Mudzakarah Hukum Tingkat Nasional MUI di Jakarta, Sabtu (23/03/2019).
Dewan Pimpinan MUI, lanjut Badriyah, memberikan masukan berkaitan dengan substansi RUU P-KS mencakup sejumlah hal.
Pertama, definisi “kekerasan seksual” perlu dirumuskan kembali karena masih terlalu luas dengan cakupan tindakan yang bersifat kumulatif atau alternatif terutama berkaitan dengan frasa “yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.
Kedua, draf pasal 11 ayat (2) berkenaan dengan bentuk/jenis kekerasan seksual perlu ditinjau kembali karena menimbulkan kesulitan implementasi, di antaranya KS berupa pemaksaan alat kontrasepsi dan pemaksaan perkawinan.
Ketiga, pasal 81 dan 82 tentang tugas dan kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan perlu dipertimbangkan kembali.
Keempat, ketentuan pidana dalam RUU yang menyimpangi ketentuan dalam KUHP perlu disinkronisasi, karena pada saat yang sama DPR juga sedang menyusun RUU KUHP yang juga mengatur masalah KS dengan ancaman hukuman yang berbeda.
“MUI berpandangan dan bersikap bahwa dalam pertimbangan konsideran dan dasar pertimbangan RUU P-KS menggunakan pendekatan paradigma konflik terkait dengan kesenjangan relasi kuasa dan relasi gender yang tidak bersumber pada nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum serta nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia,” jelas Badriyah.
Karenanya, menurut MUI, RUU ini sulit diterapkan jika menjadi undang-undang, sebab pembentukannya tidak sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang baik, yaitu asas dilaksanakan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Badriyah mengungkap, dasar hukum mengingat RUU P-KS hanya memasukkan pasal 20 dan 21 UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan DPR dalam pembentukan UU.
“Dengan mengingat tujuan dasar RUU semestinya dasar mengingat yang digunakan dalam RUU ini mencantumkan pasal 18B ayat (2), pasal 20, pasal 21, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28D ayat (1), pasal 28G, pasal 28H ayat (1), pasal 28I, pasal 28J, dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.
RUU P-KS, kata dia, sangat terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Dari sisi muatan, terangnya, RUU P-KS ternyata tumpang tindih dan tidak sinkron dengan ketentuan dalam KUHP dan setidaknya 13 UU lainnya.
“Dari sisi pengertian korban dan tahapan yang dirumuskan sejak pencegahan hingga pemulihan “cenderung sama” dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU lainnya antara lain UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya (UU Nomor 31 tahun 2014),” jelasnya. “Terdapat 60 dari 152 pasal dari RUU ini yang memuat ketentuan pidana, maka hal ini tidak konsisten dengan judul dibentuknya RUU ini.”
Dari sudut kelembagaan, lanjut Badriyah, RUU ini menimbulkan benturan antar-lembaga antara lain Kemenko PMK, KPPPA, KPAI, PPT, Komnas Perempuan, Pemda, dan lembaga lainnya.
“Pemerintah telah membahas dan mengusulkan 554 DIM dari 774 DIM dihapus. Mengacu ketentuan teknis penyusunan peraturan per-UU-an pada lampiran angka 237 UU No 12 tahun 2011, jika suatu RUU yang materi muatannya berubah sehingga mengakibatkan perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, perubahan materi lebih 50 %, atau esensinya berubah, maka peraturan per-UU-an yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut,” tutupnya. (sumber: hidayatullah)
Indeks Kabar
- Batal Digelar di Kampus Harvard, Misa Satanik Pindah ke Restoran Hong Kong
- Dalai Lama pada Suu Kyi: Bantu Muslim Rohingya!
- Umat Islam Hendaknya Kritis, Cerdas, dan Hati-hati Sebarkan Informasi
- Rakyat Taiwan Menolak Legalisasi Perkawinan Homoseksual
- Perkuat Pengawasan Penyelenggara Umrah, Kemenag Buat SIPATUH
- 1.193 Peserta MTQN Siap Bertanding
- Siapkan 10 Ribu Dai, Cinta Quran Center Tahfidz dan Da’i Institute Resmi Berdiri
- Anggota Parlemen Israel Diizinkan Masuki Tempat Suci Al-Aqsha
- MUI: Terorisme Salahi Nilai Pancasila dan Agama
- Tersangka Pembunuhan Jamaah Masjid di Kanada Mengaku Tidak Bersalah
-
Indeks Terbaru
- Lebih dari 16.000 Madrasah di Uttar Pradesh India Ditutup
- Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir-Batin
- Baznas Tolak Bantuan Palestina dari McDonald’s Indonesia
- Malam Lailatul Qadar, Malaikat Berhamburan ke Bumi
- Puasa Ramadhan Menghapus Dosa
- Paksa Muslimah Lepas Hijab saat Mugshot, Kepolisian New York Ganti Rugi Rp 278 Miliar
- Dari Martina Menjadi Maryam, Mualaf Jerman Bersyahadat di Dubai
- Al Shifa, Rumah Sakit Terbesar di Gaza Dihabisi Militer Zionis
- Tiga Macam Mukjizat Alquran
- Prof Maurice, Ilmuwan Prancis yang Jadi Mualaf Gara-Gara Jasad Firaun
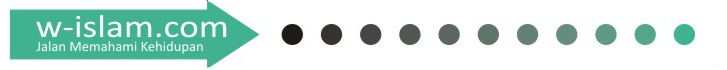
Leave a Reply